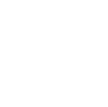Catatan Refleksi Tahun 2023 dan Gagasan Proyeksi 2024 dan Kedepan
Dibaca: 151
Penulis : Tim Adhoc Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah
IDENTIFIKASI MASALAH
Identifikasi Masalah 1: Kemunduran Demokrasi Indonesia
Freedom House merilis laporan tahunan tentang perkembangan demokrasi negara-negara di dunia. Pada dua tahun terakhir, judul yang diangkat oleh lembaga independen di Amerika ini seolah bagai kabar lelayu bagi negara-negara demokrasi. Judul laporan tahun 2019 adalah “democracy in retreat” (demokrasi dalam kemunduran) sedangkan judul yang diangkat pada laporan tahun 2020 jauh lebih menakutkan, “a leaderless struggle for democracy” (perjuangan tanpa pemimpin untuk demorkasi).Laporan dua tahun terakhir tersebut mengisyaratkan, bahwa demokrasi di dunia sedang dalam bahaya. Ramalan terjadinya kemuduran demokrasi dan bangkitnya rezim otoriter di sejumlah negara demokratis bisa saja terjadi. Namun, tulisan ini tidak akan membahas jauh ke situ karena fokus tulisan ini adalah perjalanan demokrasi di Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika.
Masih menurut laporan tahunan Freedom House, Indonesia pernah berada pada fase negara demokratis antara 2006 dan 2013. Ini merupakan prestasi baik di mana Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden saat itu mampu mendongkrak status Indonesia yang sebelum 2006 masih berada pada posisi negara semi-demokratis. Namun, sejak 2014 hingga 2022, posisi Indonesia turun kembali sebagai negara semi-demokratis. Data ini mengindikasikan, bahwa demokrasi Indonesia justru lebih berhasil di bawah kepemimpinan militer daripada sipil.
Laporan serupa juga dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam laporan Indeks Demokrasi 2019, judul yang diangkat oleh lembaga berbasis di London ini adalah “a year of democratic setbacks and popular protest” yang menegaskan, bahwa 2019 adalah tahun kemunduran demokrasi dunia dan mencuatnya gerakan protes di berbagai negara. Secara spesifik, demokrasi Indonesia saat ini dikategorikan EIU sebagai “a flawed democracy”, negara yang secara prosedural berhasil menyelenggarakan pemilu tetapi lemah dalam hal tata kelola, memiliki budaya politik yang terbelakang, partisipasi politik yang lemah, dan pemasungan terhadap kebebasan media.
Gerakan pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jalur parlemen dengan pengesahan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 serta pengesahan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja pada 05 Oktober 2020 membuat media Inggris, the Economist, mengeluarkan pernyataan keras pada 15 Oktober 2020, bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah kembali pada otoritarianisme. Apalagi terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK dinilai oleh sejumlah aktivis anti-korupsi sebagai babak akhir dari terpuruknya lembaga anti-rasuah tersebut. Dalam headline tulisan the Economist tersebut ditegaskan, bahwa meski Jokowi memotong ruwetnya birokrasi di Indonesia, tetapi presiden ini justru yang merusak institusi birokrasi itu sendiri. Dia seolah ingin membangunkan kembali rezim otoriter atau dalam istilah the Economist, Jokowi ingin menjadi seperti Soeharto.
Sosok Jokowi yang sering disebut sebagai “Man of the People” atau sosok yang mewakili kepribadian rakyat pada umumnya, kini tak sedikit dari para pendukungnya yang kecewa. Bahkan, the Economist menyebut Jokowi kini menjadi presiden yang terpencil dan jauh dari rakyatnya, terkepung dan tersandera oleh kelompok bangsawan baik kalangan elite bisnis maupun elite politik. Itulah mengapa Ben Bland menjuluki Jokowi sebagai “Man of Contradictions” (2020) yang menyatakan, pemerintahan Jokowi merupakan rezim yang penuh dengan kontradiksi dan berlawanan dengan wajah Indonesia yang modern.
Represi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap para demonstran anti-Omnibuslaw serta tindakan kekerasan dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis dan tokoh Islam juga menjadi bukti penguat, bahwa demokrasi mutakhir di Indonesia sedang berada pada kategori sakit dan membutuhkan energi besar untuk pemulihan masa penyembutan.
Identifikasi Masalah 2: Lemahnya Pelembagaan Partai Politik
Sejak runtuhnya rezim Orde Baru 1998, partai politik mulai menjadi aktor utama di panggung demokrasi elektoral selama hampir dua setengah dekade. Sejak 1999-2019, Indonesia sudah lima kali mengadakan hajatan besar demokrasi bernama pemilu dengan dinamika dan manejemen yang berbeda dari waktu ke waktu. Tak sedikit partai yang menjadi peserta pemilu datang silih berganti meski beberapa di antaranya ada yang berhasil bertahan bahkan sempat populer.
Tulisan ini mencoba untuk menganalisa dinamika perkembangan partai politik di Indonesia selama era Reformasi dengan menggunakan empat indikator pelembagaan partai politik yang dikenalkan oleh Vicky Randall dan Lars Svåsand (2002) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “party institutionalization in new democracies”. Keempat indikator tersebut adalah sistem keorganisasian (systemness), ideologi dan platform partai (value infusion), reifikasi, dan independensi partai (decisional autonomy).
- Masih Buruknya Sistem Keorganisasian. Ada tiga aspek yang akan dibahas: mekanisme pengambilan keputusan di internal partai, mekanisme penyelesaian konflik internal partai, dan mekanisme regenerasi dan rekruitmen politik. Pada aspek pertama, hampir mayoritas partai politik di Indonesia mengalami gejala yang sama, bahwa mekanisme pengambilan keputusan politik selalu bergantung pada ketokohan elite tertentu. Mekanisme organisasi seringkali tidak berlaku bahkan dikesampingkan oleh dominasi elite yang berkuasa tersebut. Dalam hal penyelesaian konflik internal partai, tak ada satu partai pun yang bisa dijadikan model percontohan. Sementara kaderisasi internal partai juga tidak berjalan efektif lantaran para elite partai mengambil jalan pintas demi mengejar syarat minimal ambang batas parlemen. Penerapan sistem sistem perwakilan berimbang daftar terbuka (Open-List Proportional Representation, OLPR) sejak 2009 hingga 2024 pada akhirnya menjadikan partai lebih memilih untuk bersikap pragmatis dengan memilih caleg dan calon kepala daerah (cakada) yang memiliki popularitas tinggi ketimbang kader ideologis yang sudah lama berjuang tetapi tidak populer.
- Pudarnya Ideologi dan Platform. Ada dua hal yang diukur di sini: sejauhmana relasi yang terjadi antara partai dan organisasi sipil/keagamaan (aktor dan pendukung) dan sejauhmana partai meyakinkan platform/ideologi partai ke anggota, pendukung, dan masyarakat luas. Meskipun relasi antara partai politik dan masyarakat sipil masih tetap terbangun di era Reformasi, tetapi kekuatan relasi tersebut tidak sedahsyat saat era Pemilu 1955 maupun Pemilu 1971.
- Kegagalan Reifikasi. Reifikasi (reification) dapat dipahami sebagai strategi partai dalam memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan di parlemen dan ekseksutif. Fenomena pengesahan RUU Omnibuslaw Ciptakerja, keinginan menggagas RUU Haluan Ideologi Pancasila, pelemahan lembaga anti-rasuah seperti KPK, pemaksaan Pilkada Serentak 2020 meski publik menolak, rencana elite untuk amandemen UUD 1945 termasuk keinginan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode serta ketergesa-gesaan pemindahan Ibu Kota Negara adalah sederet bukti gagalnya partai politik yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Belum lagi fakta buruknya praktik kebebasan sipil akibat dikebiri oleh pemerintah (dan tentu elite partai) yang berkuasa. Belum lagi sejumlah produk hukum pun seakan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, seperti UU ITE dan KUHP, yang seringkali dijadikan alat oleh penguasa untuk memukul rakyat yang kritis.Di sinilah partai politik mengalami kegagalan berkali lipat dalam memenuhi aspirasi dan harapan publik secara luas. Partai lebih ramah ke pemilik modal dan oligarkh ketimbang rakyat jelata. Wajar saja jika masyarakat kecewa bahkan cenderung tidak peduli lagi terhadap partai politik. Ini bisa berbahaya dan dapat mengancam masa depan demokrasi Indonesia.
- Lemahnya Independensi. Independensi/kemandirian partai politik diukur dengan dua aspek: 1) independensi partai dari pemimpin yang kharismatik dan kuat dalam proses pengambilan kebijakan; dan 2) independensi partai dari kekuatan cukong (pemilik modal) dan kaum oligarkh.Publik hampir sulit membedakan antara PDIP dan Megawati, Partai Demokrat dan SBY, Gerindra dan Prabowo Subianto, Nasdem dan Surya Paloh, PKB dan Muhaimin Iskandar, dan seterusnya. Semua keputusan politik hampir selalu tergantung pada elite kuat tersebut sehingga mekanisme organisasi di tubuh partai seakan tidak berlaku lagi. Di sinilah awal menjamurnya otoritarianisme di internal partai-partai. Modernisasi partai politik selama era Reformasi seperti masih jauh dari harapan demokrasi. Karena itu, diperlukan regulasi tentang perlunya pembatasan periode kepemimpinan ketua umum partai.Sementara itu, partai pun masih belum bisa terbebas dari kekuatan cukong atau pemilik modal dan kaum oligarkh. Cukong dan oligarkh bisa saja langsung bertindak sebagai pemilik partai atau mereka sekadar menjadi orang di balik layar yang selalu mendanai program-program partai. Akibatnya, dalam proses pembuatan produk legislasi (Undang-Undang/Perda) dan pembuatan anggaran, anggota legislatif sebagai kepanjangantangan partai politik di parlemen memiliki kecenderungan lebih ramah kepada kepentingan pemilik modal daripada mendahulukan aspirasi rakyat yang hanya dihargai selembar rupiah pada saat Pemilu/Pilkada.
Identifikasi Masalah3: Sistem Pemilu yang Begitu Liberal
Sejak pertama Indonesia menyelenggarakan pemilu pada 1955, sistem pemilu yang digunakan adalah Closed List Proportional Representation (CLPR) atau dikenal juga dengan sebutan “sistem proporsional tertutup”. Sistem ini berlaku juga selama era Orde Baru dan berakhir digunakan pada Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004, sistem yang digunakan memang masih CLPR tetapi mengalami modifikasi sehingga ada unsur sistem Open List Proportional Representation (OLPR) atau dikenal dengan sebutan “sistem proportional terbuka”. Barulah sejak Pemilu 2009-2024, sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem OLPR murni.
Munculnya penerapan sistem OLPR sejak 2009 sebenarnya berangkat dari kelemahan sistem CLPR yang dianggap seperti memilih kucing dalam karung. Artinya, pemilih tidak bisa mempengaruhi keterpilihan caleg secara langsung karena pemilih hanya diizinkan untuk memilih partai saja sehingga di bawah sistem CLPR, hanya caleg yang berada di nomor urut terkecil saja yang mempunyai peluang besar untuk masuk ke parlemen. Sementara jika caleg yang disukai pemilih berada pada nomor urut besar, sulit peluang untuk terpilih. Di sinilah yang menjadi titik kritis keinginan sejumlah pihak terutama pegiat LSM kepemiluan pada saat itu. Selain persoalan lemahnya CLPR pada aspek ketidakmampuan pemilih dalam mengintervensi keterpilihan caleg, CLPR juga tidak bisa melibatkan caleg non-partai untuk terpilih sehingga hanya caleg yang dekat ke elite partai saja yang memiliki peluang besar mendapatkan nomor urut terkecil.
Namun demikian, OLPR tidak sepi dari kritik juga. Sistem OLPR dianggap seperti pertarungan pasar bebas antar-kandidat yang kuat saja. Siapa yang punya modal banyak, mereka menang. Mereka yang terpilih seringkali bukan karena kualitas tetapi karena isi tas. Fragmentasi tidak hanya terjadi caleg antar-partai, tetapi caleg sesama internal partai, bahkan fragmentasi yang terakhir ini jauh lebih keras dibanding antar-partai. Selain itu, partai tidak lagi memiliki peran kuat untuk menentukan kemenangan kandidat karena kemenangan seseorang seratus persen lebih diintervensi oleh suara terbanyak.
Dampaknya, politik uang dan sejumlah pelanggaran pemilu lainnya kerap dilakukan para caleg yang bekerjasama dengan brokers jualan suara. Sistem OLPR juga cenderung memberikan peluang ke para konglomerat dan pemilik modal memberikan bantuan keuangan kepada para kandidat sehingga kandidat yang terpilih tidak murni atas perjuangan sendiri tetapi meninggalkan hutang balas budi yang harus mereka bayar setelah terpilih. Inilah titik rawan yang dapat mengakibatkan terjadi korupsi, suap, dan sejenisnya. Saat ini, sejumlah pihak menginginkan untuk kembali lagi ke sistem CLPR yang dianggap lebih mendorong penguatan kelembagaan partai. Namun demikian, tak sedikit juga yang tetap mempertahankan sistem OLPR karena dianggap melibatkan pemilih menjadi penentu kemenangan caleg. Lalu mana yang terbaik dan relevan?
Dalam konteks pemilu di Indonesia, perdebatan dua kubu antara OLPR dan CLPR memang tidak akan pernah selesai. Semua pihak memiliki alasan masing-masing. Partai politik mempunyai kepentingannya sendiri jika memberikan usulan sistem mana yang terbaik. Karena itu, perlu titik tengah untuk memodifikasi sistem List Proportional Representation (LPR) agar tidak terjebak pada titik ekstrim antara tertutup dan terbuka.
Identifikasi Masalah4: Krisis Ekologis dan Kejahatan Ekosida
Saat ini Indonesia sedang mengalami krisis ekologis berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, banjir bandang, longsor, dan konflik agraria. Dalam presentasi Parid Ridwanuddin (peneliti WALHI) pada forum Regional Meeting LHKP Muhammadiyah di Kota Makassar, 2 September 2023, dijelaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam telah berhasil dilakukan di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan dan saat ini sedang menyasar Kawasan Indonesia Timur terutama untuk pengembangan industri nikel dalam rangka memenuhi pasar mobil listrik dunia. Pemerintah telah memberikan izin skala besar untuk pertambangan, izin pembukaan hutan, eksploitasi pesisir-laut-pulai kecil dalam rangka memenuhi target investasi. Dampak dari itu, terjadi degradasi lingkungan hidup yang parah serta mempercepat bencana banjir dan longsor.
Menurut data BNPB, sejak 2000 hingga 2019, telah terjadi sebanyak 9.394 kali banjir yang menyebabkan 5.023 orang meninggal dunia, 263.605 orang mengalami luka-luka, dan memaksa 29.537.476 orang mengungsi. Selama 19 tahun ini juga, telah terjadi 5.461 kali bencana longsor yang mengakibatkan 2.991 orang meninggal dunia, 2.944 orang terluka, dan memaksa 278.991 orang mengungsi. Dari data Izin Usaha Pertambangan per November 2021, tercatat setidaknya ada 2.919.870,93 hektar (1.405 IUP) wilayah pesisir, dan 687.909,01 hektar (324 IUP) wilayah laut Indonesia telah dikapling-kapling oleh izin-izin tambang. Lebih dari 35 ribu keluarga nelayan terdampak proyek ini. Dampak proyek pertambangan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat masif ini, setidaknya ada 6.081 desa pesisir yang kawasan perairannya telah tercemari limbah pertambangan.
Muhammadiyah di bawah koordinasi M. Busyro Muqoddas (ketua PP Muhammadiyah) selalu mendampingi masyarakat korban terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) milik pemerintah yang terjadi di sejumlah lokasi seperti di Desa Wadas Purworejo (Jawa Tengah), Desa Pakel Banyuwangi (Jawa Timur), Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), dan Nagari Air Bangis Pasaman Barat (Sumatera Barat). Pendampingan dilakukan juga di berbagai lokasi lainnya. Dengan menggandeng berbagai pihak yang masih mempunyai jiwa kemanusiaan, tugas ini secara kelembagaan di Muhammadiyah didampingi oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), Majelis Hukum dan HAM (MHH), dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP).
Inilah fakta mutakhir. Krisis ekologis telah dan masih terjadi karena adanya eksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diberikan izin oleh pemerintah. Lebih dari 80 persen bencana ekologis berasal dari konsesi yang diberikan pemerintah untuk investasi skala besar khususnya di kawasan Indonesia Timur. Tentu bencana ekologis ini memiliki dampak jangka panjang terutama bagi generasi anak cucu kita kelak. Krisis ekologis ini dalam pandangan Fransz Broswimmer (sosiolog lingkungan, Universitas Hawai) disebut sebagai fenomena ekosida, yaitu pembunuhan dan pemusnahan terhadap sebuah ekosistem termasuk mereka yang ikut serta dalam membuat kebijakan dan mengonsumsinya secara masif. Praktik ekosida dilakukan secara sistematis yang menyebabkan musnahnya fungsi ekologis, sosial, dan budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia.
Setidaknya ada tiga aspek penting suatu perbuatan disebut sebagai ekosida. Pertama, dampak kejahatan itu sangat panjang terhadap suatu satuan dan fungsi kehidupan serta tidak dapat dipulihkan kembali. Kedua, terdapat satuan fungsi yang musnah pada suatu rangkaian kehidupan dari kondisi semula. Ketiga, terdapat penyimpangan fisik dan psikis manusia. Karena itu, Parid mengatakan, bahwa ekosida sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan modern yang setara dengan kejahatan kemanusiaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari akibatnya yang sangat parah terhadap lingkungan hidup dan kehidupan manusia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bahkan sejumlah organisasi lingkungan hidup internasional seperti Global Witness menyerukan pelakunya diadili di Den Haag besama dengan penjahat perang.
Dengan meminjam konsep ekosida di atas, UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan peraturan turunannya memiliki potensi besar untuk dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan ekosida. UU tersebut menciptakan ekosistem yang dapat mengakibatkan eksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam sehingga berdampak pada bencana ekologis dalam jangka waktu yang lama. Kebijakan PSN yang mengakibatkan tindakan intimidasi oleh aparat pemerintah kepada rakyat seperti yang terjadi di Wadas, Pakel, dan Air Bangis adalah fakta yang mengarah pada indikasi tindakan ekosida.
REFLEKSI TAHUN 2023: DEMOKRASIDIKEBIRI,HAMDIHANTAM,PSNDIIDOLAKAN
Berbekal hati dan pikiran yang jernih, kita semua sadar bahwa bangsa ini sedang sekarat. Maka dari itu, kami uraikan dan maklumatkan secara ringkas pandangan dan sikap pokok kami sebagai masyarakat sipil terhadap perkembangan bangsa Indonesia, sebagai berikut:
- Para pakar, pengamat, jurnalis, pegiat demokrasi dan HAM, termasuk didalamnya para aktivis, kaum muda, masyarakat adat, pegiat komunitas, dan segelintir kecil pemuka agama telah menyebut atau menjadi saksi atas betapa buruk dan suramnya masa depan penegakan hukum, kebebasan masyarakat sipil, dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi sepanjang tahun2023.
- Kemerosotan, peluruhan, dan kematian secara mengenaskan penegakan demokrasi di Indonesia melalui suksesi politik kekeluargaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan pencawapresan putra kandungnya yakni Gibran Rakabuming Raka dengan memanfaatkan Anwar Usman ketika menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, adik iparnya, dapat membawa Indonesia ke masa suram instabilitas politik nasional dengan bangkitnya otoritarianisme militeristik pasca Pilpres 2024 sebagaimana pernah terjadi padadekade1960-an.
- Penyelamatan demokrasi elektoral dan perlindungan serta pengembangan masyarakat madani adalah duavariabel penting untuk menyelamatkan Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya Presiden Joko Widodo dan segenap elemen Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama yang berada di bawah Polri dan TNI untuk menjaga netralitas Pemilu 2024 demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkeadilan.
- Menekan Bawaslu dan aparat penegak hukum agar tidak normatif dalam menyikapi temuan PPATK yang membuka kedok pendanaan kampanye ilegal dan jual-beli suara jelang Pemilu2024. Bawaslu dan aparat penegak hukum harus mengambil keputusan yang tepat dan maslahat untuk kepentingan Rakyat Indonesia. Apalagi, PPATK telah mengidentifikasi aliran uang triliunan rupiah yang bersumber dari uang masyarakat yang dicairkan melalui pinjaman modal aktif, dan berasal dari kejahatan pertambangan, lingkungan, sertajudi. Selainitu, juga temuan PPATK terkait penggunaan uang tunai dari ratusan ribu safedepositbox dibank BUMN dan swasta sejak Januari 2022 hingga 30 Desember 2023.
- Menekan Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bebas dari politik uang dan mobilisasi dukungan yang dikemas dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bansos. BLT el-Nino yang dialokasikan sebesar 7,52 triliun yang disalurkan November dan Desember 2023 ditengarai dapat menjadi pintu masuk mobilisasi dukungan masyarakat terhadapsalah satu kandidat Capres dan Cawapres yang terlibat kepentingan dengan Presiden Joko Widodo.
- Mendesak Pemerintah untuk mengerem ambisi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terbukti telah menelan korban jiwa dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana berlangsung di antaranya di Air Bangis Sumatera Barat, Rempang Kepulauan Riau,Wadas Purworejo, dan Pakel Banyuwangi.
- Mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan penahanan terhadap masyarakat yang berjuang mempertahankan kelestarian lingkungan dari malapetaka kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan peran dan fungsi KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dipreteli kekokohannya sebagai lembaga anti rasuah terpercaya masyarakat akibat Revisi UU KPK.
AGENDA MENDESAK UNTUK PROYEKSI 2024 DAN KEDEPANNYA
Berdasarkan data dan fakta di atas, sejumlah agenda mendesak perlu dirumuskan agar proses konsolidasi demokrasi Indonesiadapat diraih lebih baik daripada sebelumnya. Berikut ini sejumlah agenda mendesak:
- Merevisi serta melengkapi Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Banyak aspek yang harus dimasukkan pada UU revisi, seperti pembatasan periode kepemimpinan, pengaturan keuangan partai, pola rekruitmen anggota, dan lain sebagainya. Publik dan masyarakat ilmiah dituntut untuk mendesak partai politik agar segera melakukan revisi UU tersebut. Pada kenyataannya, partai terkesan enggan untuk melakukannya karena bisa saja revisi tersebut justru merugikan bahkan bisa mengancam posisi status quo mereka.
- Apakah sistem multi-partai di Indonesia merusak iklim demokrasi yang sehat dan dianggap tidak efektif? Tentu tidak. Pengalaman sistem multi-partai di sejumlah negara Eropa masih menunjukkan pemerintahan yang efektif. Justru keragaman budaya Indonesia harus dikanalisasi oleh kekuatan politik yang beragam agar tidak terjadi gerakan separatis di berbagai daerah akibat aspirasi politik mereka tidak terakomodasi. Munculnya partai lokal di Aceh maupun tidak adanya pemilihan gubernur di Yogyakarta adalah cerminan keberagaman praktik demokrasi di negara bhinneka seperti Indonesia. Sistem demokrasi tidak harus dipahami secara tunggal tetapi bisa beragam dengan tetap mengacu pada prinsip utamanya. Karena itu, amang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen adalah batas maksimal dan jangan ditambah lagi agar supaya partai menengah dan kecil tidak terpental dari Senayan karena mereka bagian dari kanal kekuatan politik tertentu di republik ini. Dengan kata lain, penyederhaan partai sebagai bentuk penguatan sistem presidensiil bukanlah ide tepat dan bijak.
- Jika partai politik adalah kesebelasan, maka pemilu adalah arena pertandingannya. Karena itu, sistem pemilu harus mendukung penguatan dan modernisasi kelembagaan partai politik. Karena itu, praktik model keserentakan pemilu yang relevan untuk Indonesia seharusnya dibagi menjadi dua: keserentakan pemilu nasional (Pilpres, Pileg DPR RI, dan Pemilihan DPD RI) dan keserentakan pemilu lokal (Pilgub, Pileg DPRD Provinsi, Pilbub/Pilwalikot, dan Pileg DPRD Kabupaten/Kota) yang berjarak 2,5 tahun di antara keduanya. Sebagai catatan tambahan, pada pemilu serentak nasional, Pilpres didahuluan yang kemudian disusul beberapa bulan berikutnya oleh Pileg DPR RI dan DPD RI. Karena itu, praktik model keserentakan pemilu yang pernah terjadi pada 2019 dan akan diulangi lagi pada 2024 bukanlah ide yang efektif. Itu adalah bentuk overdosis demokrasi. Hasilnya, justru anti-klimaks demokrasi.
- Sistem representasi proporsional yang moderat dengan berpijak pada system OLPR yang dimodifikasi adalah pilihan sistem yang relevan untuk konteks Indonesia. Pertimbangan utama masih memilih sistem OLPR ini adalah kesuksesan negara-negara demokrasi mapan seperti Norwegia yang juga menggunakan OLPR serta stabilitas demokrasi di negara-negara penganut sistem OLPR ketimbang sistem pemilu yang lain. Dengan sistem keserentakan pemilu sebagaimana diusulkan pada poin nomor tiga di atas, maka beban kerja penyelenggara pemilu tidak menumpuk. Selain itu, pemilih juga tidak kesulitan dalam menentukan pilihan mereka karena hanya ada tiga surat suara pada pemilu serentak nasional dan empat surat suara pada pemilu serentak lokal. Implikasinya, penyederhanaan surat suara sepertinya tidak begitu diperlukan lagi. Partai politik pun bisa mempersiapkan calon-calon terbaik mereka baik untuk nasional maupun daerah karena ada jeda waktu yang optimal untuk proses rekruitmen dan seleksi. Jikalau praktik money politics dipersoalkan dalam sistem OLPR, regulasinya perlu diperkuat sehingga revisi UU Pemilu adalah sebuah keniscayaan. Revisi tersebut perlu dilakukan terhadap definisi politik uang serta para pelakunya dan juga perlunya penambahan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi atas praktik politik uang. Gagasan nomor tiga dan empat ini akan diulas secara detail oleh penulis pada kesempatan yang lain.
Demikian gagasan dari kami terkait dengan situasi mutakhir seputar politik dan kebangsaan yang kami analisa secara utuh dan komprehensif untuk menjadi catatan para pihak di Republik ini.
Tags: